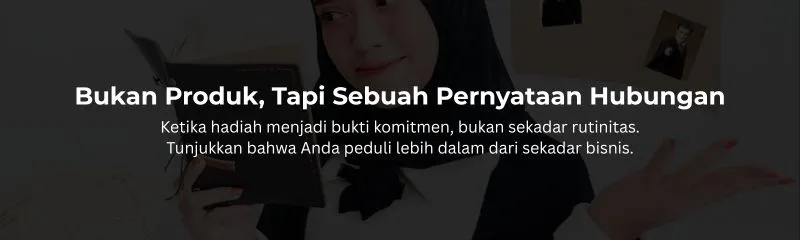Kebudayaan adalah kata yang kita gunakan setiap hari, namun definisinya seringkali terasa licin dan sulit dipahami. Ia adalah udara yang kita hirup dalam masyarakat, sebuah kekuatan tak terlihat yang membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Untuk memahami esensinya, kita harus kembali ke salah satu definisi paling fundamental dalam ilmu antropologi, yang dirumuskan oleh E.B. Tylor pada tahun 1871. Definisinya tentang kebudayaan sebagai “keseluruhan yang kompleks” menjadi titik awal yang merevolusi cara kita memandang masyarakat manusia. Namun, seperti kebudayaan itu sendiri, pemahaman kita tentang konsep ini terus berevolusi, bergerak dari pandangan klasik yang statis menuju pemahaman modern yang jauh lebih dinamis, cair, dan terhubung secara global.
Membedah Definisi Klasik E.B. Tylor: Arsitektur “Keseluruhan yang Kompleks”
Dalam karyanya yang monumental, Primitive Culture, Sir Edward Burnett Tylor meletakkan fondasi bagi studi antropologi modern dengan sebuah definisi yang hingga kini masih menjadi rujukan utama. Ia menyatakan, **”Kebudayaan atau Peradaban, yang dipahami dalam pengertian etnografisnya yang luas, adalah keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain apa pun yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.”** Definisi ini, pada masanya, adalah sebuah terobosan. Ia secara radikal menyatakan bahwa setiap masyarakat, tidak peduli seberapa “primitif” menurut standar Eropa saat itu, memiliki sebuah sistem yang terstruktur dan komprehensif yang layak untuk dipelajari secara ilmiah.
Frasa kunci dalam definisi Tylor adalah “keseluruhan yang kompleks” (complex whole). Ini menyiratkan bahwa kebudayaan bukanlah sekadar kumpulan elemen yang acak, melainkan sebuah sistem yang terintegrasi di mana setiap bagian saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Perubahan dalam sistem kepercayaan, misalnya, dapat memengaruhi praktik ekonomi, struktur keluarga, dan bahkan ekspresi seni. Pandangan holistik inilah yang menjadi ciri khas dari pendekatan antropologi, yang selalu berusaha memahami fenomena dalam konteksnya yang lebih luas.
Definisi Tylor juga secara tegas menyatakan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang “diperoleh” (acquired), bukan diwariskan secara biologis. Ini adalah pemisahan krusial antara ras dan budaya, yang menantang pandangan rasis yang umum pada abad ke-19. Dengan menekankan bahwa kebudayaan adalah hasil dari pembelajaran dalam sebuah masyarakat, Tylor membuka jalan bagi pemahaman bahwa keragaman manusia adalah produk dari sejarah, lingkungan, dan interaksi sosial yang berbeda, bukan dari perbedaan biologis yang inheren. Dari definisi klasik ini, kita dapat mengurai beberapa kualitas fundamental dari kebudayaan.
Kebudayaan itu Dipelajari (Learned), Bukan Diwariskan
Kualitas paling mendasar dari kebudayaan adalah bahwa ia tidak tertanam dalam gen kita. Kita tidak dilahirkan dengan pengetahuan tentang cara berbicara dalam bahasa tertentu, norma-norma kesopanan, atau sistem kepercayaan. Sebaliknya, kita memperoleh semua ini melalui proses pembelajaran seumur hidup yang oleh para antropolog disebut **enkulturasi**. Proses ini dimulai sejak saat kita lahir, di mana kita secara sadar dan tidak sadar menginternalisasi tradisi dari generasi sebelumnya. Kita belajar dengan mengamati, mendengarkan, berinteraksi, dan diajari secara langsung.
Proses enkulturasi membentuk kepribadian dan perilaku kita secara mendalam. Praktik pengasuhan anak, misalnya, sangat bervariasi antar budaya dan memiliki dampak besar pada perkembangan individu. Dalam beberapa masyarakat, anak-anak didorong untuk menjadi mandiri sejak usia dini, sementara di masyarakat lain, ketergantungan pada kelompok lebih ditekankan. Pembelajaran ini terjadi melalui bahasa, ritual, cerita, dan bahkan melalui cara kita menggunakan ruang dan waktu. Kebudayaan menjadi “lensa” yang kita gunakan untuk melihat dan menafsirkan dunia, seringkali tanpa kita sadari.
Karena kebudayaan itu dipelajari, ia juga bersifat fleksibel dan dapat berubah. Individu dapat mempelajari lebih dari satu budaya, dan budaya itu sendiri dapat mengadopsi elemen-elemen baru dari budaya lain melalui proses yang disebut akulturasi. Kemampuan manusia untuk belajar dan beradaptasi inilah yang memungkinkan spesies kita untuk berkembang di hampir setiap lingkungan di muka bumi, dengan menciptakan solusi budaya yang beragam untuk tantangan yang berbeda.
Kebudayaan itu Dibagikan (Shared), Namun Tidak Merata
Kebudayaan, pada hakikatnya, adalah fenomena sosial. Ia tidak dapat eksis hanya dengan satu individu; ia membutuhkan sebuah komunitas atau masyarakat yang secara kolektif mempraktikkan dan meneruskannya. Adanya pemahaman bersama tentang makna simbol, nilai, dan norma perilakulah yang memungkinkan anggota masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan hidup bersama secara efektif. Bahasa adalah contoh paling jelas dari kebudayaan yang dibagikan; tanpa kesepakatan bersama tentang arti kata-kata, komunikasi akan mustahil.
Namun, penting untuk dipahami bahwa “dibagikan” tidak berarti “dibagikan secara seragam oleh semua orang”. Dalam masyarakat mana pun, pengetahuan dan praktik budaya didistribusikan secara tidak merata. Para antropolog mengidentifikasi beberapa mode distribusi: ada “universal” (yang dibagikan oleh hampir semua orang, seperti bahasa nasional), “alternatif” (berbagai cara yang dapat diterima untuk melakukan sesuatu), “spesialisasi” (pengetahuan yang hanya dimiliki oleh subkelompok tertentu, seperti dokter atau pemuka agama), dan “kekhasan individu” (kebiasaan unik yang hanya dimiliki oleh segelintir orang).
Masyarakat Aborigin Warlpiri di Australia, misalnya, secara sistematis mendistribusikan pengetahuan keagamaan berdasarkan usia dan jenis kelamin, di mana beberapa pengetahuan ritual dianggap sangat sakral dan hanya dapat diakses oleh para tetua. Di masyarakat Barat modern, kita melihat distribusi ini dalam bentuk subkultur (seperti komunitas punk atau gamer) dan kontra-budaya (yang secara aktif menentang nilai-nilai dominan). Keragaman internal ini menunjukkan bahwa kebudayaan bukanlah entitas monolitik, melainkan sebuah mosaik yang dinamis dari pemahaman yang tumpang tindih dan terkadang saling bertentangan.
Kebudayaan itu Simbolik (Symbolic), Jaring-jaring Makna
Antropolog Clifford Geertz secara puitis menggambarkan manusia sebagai “hewan yang terjerat dalam jaring-jaring makna yang ditenunnya sendiri.” Jaring-jaring inilah kebudayaan. Kualitas simbolik adalah inti dari kebudayaan. Sebuah simbol adalah sesuatu, baik itu verbal maupun non-verbal, yang secara sewenang-wenang mewakili sesuatu yang lain. Tidak ada hubungan yang alami atau logis antara simbol dan apa yang diwakilinya; hubungan itu diciptakan dan disepakati secara sosial.
Bahasa adalah sistem simbol yang paling kompleks dan penting, tetapi simbolisme meresap ke dalam setiap aspek kehidupan. Sebuah bendera hanyalah selembar kain berwarna, tetapi ia dapat membangkitkan emosi patriotisme yang kuat. Warna putih dapat melambangkan kesucian dalam satu budaya dan duka dalam budaya lain. Bahkan objek sehari-hari dapat menjadi simbol yang kuat. Di dunia korporat, misalnya, sebuah notebook kustom dari Hibrkraft yang diberikan kepada setiap karyawan baru bukan lagi sekadar alat tulis. Ia menjadi simbol dari budaya perusahaan: mungkin budaya inovasi yang menghargai pencatatan ide, budaya keteraturan yang menghargai perencanaan, atau budaya apresiasi yang menunjukkan bahwa setiap individu dihargai sejak hari pertama.
Melalui sistem simbolik ini, kebudayaan membentuk cara kita memandang realitas. Ia memberikan kita kategori-kategori untuk memahami dunia, seperti apa yang dianggap “baik” atau “buruk”, “sopan” atau “tidak sopan”, “alami” atau “tidak alami”. Karya seni Aborigin Australia adalah contoh yang sangat baik dari simbolisme budaya, di mana titik-titik dan garis-garis yang tampaknya abstrak sebenarnya adalah peta naratif yang kompleks tentang mitologi, geografi, dan silsilah.
Kebudayaan itu Terintegrasi (Integrated), Sebuah Sistem yang Saling Terhubung
Mengulangi frasa kunci Tylor, kebudayaan adalah “keseluruhan yang kompleks”. Ini berarti bahwa berbagai elemen kebudayaan tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Para antropolog sering menganalisis sistem ini ke dalam empat bidang fungsional utama: ekonomi (cara orang mencari nafkah), kekerabatan (cara keluarga dan hubungan sosial diatur), politik (cara kekuasaan didistribusikan dan keputusan dibuat), dan religi (sistem kepercayaan dan pandangan dunia).
Keterkaitan ini berarti bahwa perubahan di satu area dapat menyebabkan efek riak yang luas di area lain, seringkali dengan cara yang tidak terduga. Misalnya, pengenalan teknologi pertanian baru (perubahan ekonomi) dapat secara drastis mengubah struktur keluarga tradisional (perubahan kekerabatan) karena orang tidak lagi perlu bekerja bersama di ladang. Perubahan ini, pada gilirannya, dapat menantang struktur kekuasaan yang ada (perubahan politik) dan bahkan sistem kepercayaan yang terkait dengan panen dan alam (perubahan religi).
Karena sifatnya yang terintegrasi, kebudayaan cenderung memiliki seperangkat nilai inti (core values) yang menopang dan menyatukan berbagai aspeknya. Nilai-nilai ini, seperti individualisme di Amerika Serikat atau kolektivisme di banyak masyarakat Asia, tercermin dalam berbagai institusi dan praktik sosial, mulai dari cara anak-anak dibesarkan hingga cara bisnis dijalankan. Memahami keterkaitan ini sangat penting untuk menghindari intervensi yang naif yang mungkin memiliki konsekuensi negatif yang tidak diinginkan.
Kebudayaan itu Adaptif (Adaptive), Mekanisme Bertahan Hidup
Pada tingkat yang paling fundamental, kebudayaan adalah mekanisme adaptasi utama bagi spesies manusia. Berbeda dengan hewan lain yang mengandalkan adaptasi biologis untuk bertahan hidup, manusia terutama mengandalkan adaptasi budaya. Kita tidak menumbuhkan bulu tebal di iklim dingin; kita menciptakan pakaian, tempat tinggal, dan sistem pemanas. Kita tidak mengembangkan sayap untuk melintasi jarak jauh; kita menciptakan perahu, mobil, dan pesawat terbang.
Setiap aspek kebudayaan dapat dilihat sebagai bagian dari strategi adaptasi ini. Perilaku ekonomi, misalnya, adalah cara masyarakat beradaptasi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dasar akan makanan, air, dan tempat tinggal. Sistem kekerabatan dan pernikahan menyediakan jaringan sosial yang stabil untuk membesarkan generasi berikutnya. Sistem politik menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan mengorganisir tindakan kolektif. Bahkan sistem kepercayaan dan religi dapat berfungsi sebagai mekanisme adaptif dengan memberikan makna, harapan, dan kohesi sosial di hadapan ketidakpastian hidup.
Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua aspek budaya bersifat adaptif. Beberapa kebiasaan atau tradisi yang pernah adaptif di masa lalu mungkin menjadi maladaptif di lingkungan yang berubah. Misalnya, pola konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi mungkin menjadi maladaptif dalam menghadapi perubahan iklim. Kemampuan sebuah budaya untuk membuang praktik yang maladaptif dan menciptakan solusi baru adalah kunci dari ketahanan dan keberlanjutan jangka panjangnya.
| Aspek | Pandangan Klasik (Tylorian) | Pandangan Kontemporer |
|---|---|---|
| Sifat Budaya | Cenderung dilihat sebagai entitas yang stabil, koheren, dan “dimiliki” oleh suatu masyarakat. | Dilihat sebagai proses yang dinamis, cair, seringkali terfragmentasi dan penuh kontradiksi. |
| Batasan | Seringkali diasosiasikan dengan wilayah geografis atau kelompok etnis yang jelas. | Batasannya kabur, terus-menerus melintasi batas negara melalui migrasi dan media (sirkulasi). |
| Proses | Fokus pada pewarisan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya (enkulturasi). | Fokus pada bagaimana budaya secara aktif “diproduksi” dan “dipraktikkan” oleh individu dan institusi. |
| Analisis | Menganalisis budaya sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dan fungsional. | Menganalisis hubungan antara budaya dengan kekuasaan, pasar, dan media global. |
| Realitas | Cenderung melihat budaya sebagai realitas objektif yang dapat didokumentasikan. | Mengakui bahwa “kebudayaan” itu sendiri adalah konsep yang dibangun secara sosial dan interpretatif. |
Evolusi Konsep Kebudayaan: Dari Entitas Statis ke Proses yang Dinamis
Meskipun definisi klasik Tylor memberikan fondasi yang tak ternilai, pemahaman antropologi tentang kebudayaan telah berevolusi secara signifikan, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Para antropolog kontemporer, yang dihadapkan pada dunia yang semakin terglobalisasi dan saling terhubung, menyadari bahwa model kebudayaan sebagai sistem yang tertutup, homogen, dan stabil tidak lagi memadai. Pandangan modern menekankan sifat kebudayaan yang jauh lebih cair, kompleks, dan dinamis.

Evolusi ini didorong oleh pengakuan bahwa kebudayaan tidak hanya “ada” di luar sana untuk ditemukan dan didokumentasikan. Sebaliknya, ia secara terus-menerus **diproduksi, dipraktikkan, dan diedarkan**. Individu bukanlah penerima pasif dari tradisi; mereka adalah agen aktif yang menafsirkan, menegosiasikan, dan terkadang menentang norma-norma budaya dalam tindakan mereka sehari-hari. Institusi-institusi kuat seperti perusahaan, pemerintah, dan media juga memainkan peran besar dalam memproduksi dan menyebarkan bentuk-bentuk budaya tertentu.
Pergeseran fokus ini membawa analisis kebudayaan ke dalam ranah kekuasaan, pasar, dan media. Para antropolog kini mempelajari bagaimana iklan membentuk hasrat konsumen, bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi identitas etnis, atau bagaimana media sosial menciptakan komunitas virtual baru dengan norma dan bahasanya sendiri. Pemahaman baru ini mengakui bahwa kebudayaan selalu berada dalam keadaan “menjadi” (in a state of becoming), bukan sebagai entitas yang sudah “jadi”.
Kebudayaan sebagai Proses: Diproduksi, Dipraktikkan, dan Diedarkan
Pandangan kontemporer melihat kebudayaan bukan sebagai seperangkat aturan yang memaksa, melainkan sebagai “tindakan yang terstruktur secara sosial”. Konsep **habitus** dari sosiolog Pierre Bourdieu sangat berpengaruh di sini. Habitus adalah seperangkat disposisi, keterampilan, dan cara pandang yang kita peroleh melalui pengalaman hidup dalam lingkungan sosial tertentu. Ia bukanlah seperangkat aturan yang kita ikuti secara sadar, melainkan semacam “rasa permainan” (feel for the game) yang secara intuitif memandu tindakan dan strategi kita dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kata lain, kita tidak hanya mempelajari “aturan” budaya; kita menginternalisasi cara “menjadi” orang yang berbudaya dalam masyarakat kita. Habitus inilah yang membuat tindakan kita terasa “alami” atau “masuk akal” bagi kita dan orang lain di sekitar kita. Namun, karena habitus dibentuk oleh pengalaman, ia juga dapat berubah seiring waktu ketika kita menghadapi situasi baru. Ini menjelaskan bagaimana individu dapat beradaptasi dengan budaya baru sambil tetap membawa jejak dari latar belakang mereka.
Selain diproduksi dan dipraktikkan, kebudayaan juga terus-menerus **diedarkan** atau bersirkulasi. Di dunia modern, kebudayaan tidak lagi terikat pada satu lokasi geografis. Ia bergerak melintasi perbatasan melalui rantai migrasi, jaringan perdagangan, media global, dan pariwisata. Musik K-Pop yang dinikmati di Jakarta, serial anime Jepang yang ditonton di Brazil, atau yoga India yang dipraktikkan di New York adalah contoh nyata dari sirkulasi budaya global ini. Ini berarti bahwa “sebuah kebudayaan” tidak dapat lagi dipetakan secara rapi ke dalam satu wilayah atau masyarakat yang terbatas.
Globalisasi dan “Glokalisasi”: Meleburnya Batasan Budaya
Salah satu konsep kunci untuk memahami dinamika budaya di era modern adalah **glokalisasi**. Istilah ini adalah gabungan dari “globalisasi” dan “lokalisasi”, dan ia menangkap sebuah proses yang penting: meskipun ada proses global yang meluas (seperti penyebaran kapitalisme atau internet), manifestasi dan dampaknya selalu bersifat lokal dan unik. Dengan kata lain, globalisasi tidak serta merta menciptakan budaya dunia yang homogen; sebaliknya, ia berinteraksi dengan kondisi lokal untuk menghasilkan bentuk-bentuk hibrida yang baru.
Contoh klasik dari glokalisasi adalah restoran cepat saji seperti McDonald’s. Meskipun merek dan model bisnisnya bersifat global, menunya seringkali diadaptasi untuk memenuhi selera lokal. Di India, Anda akan menemukan Maharaja Mac (yang menggunakan ayam, bukan sapi), dan di Indonesia, Anda akan menemukan McSpicy atau menu dengan nasi. Ini menunjukkan bagaimana sebuah fenomena global (budaya makanan cepat saji Amerika) mengambil bentuk lokal yang khas saat ia berinteraksi dengan tradisi kuliner yang sudah ada.
Konsep glokalisasi menantang gagasan sederhana tentang imperialisme budaya, yang berpendapat bahwa budaya Barat akan menghapus semua budaya lokal. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Orang-orang di seluruh dunia secara aktif mengambil, menafsirkan, dan memodifikasi produk dan ide global agar sesuai dengan konteks mereka sendiri. Proses ini memastikan bahwa realitas budaya akan selalu tetap bersifat lokal, bahkan di tengah dunia yang semakin terhubung secara global.
Komposisi Suku Bangsa Terbesar di Indonesia (Sensus BPS 2010)
Realitas yang Dibangun: Refleksi Kritis Antropologi
Evolusi terakhir dalam pemahaman tentang kebudayaan adalah sebuah giliran reflektif, di mana para antropolog mulai mempertanyakan konsep-konsep dasar dari disiplin mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa “kebudayaan” dan “masyarakat” bukanlah realitas objektif yang ada di luar sana, melainkan konsep atau “fiksi akademis” yang diciptakan oleh para antropolog untuk memahami dunia. Cara seorang antropolog menulis tentang sebuah budaya (proses yang disebut etnografi) tidak pernah bisa sepenuhnya objektif; ia selalu dibentuk oleh latar belakang, teori, dan pilihan naratif dari si penulis.
Gerakan kritis ini, yang terlihat dalam karya-karya penting seperti The Invention of Culture oleh Roy Wagner dan Writing Culture yang diedit oleh James Clifford dan George Marcus, menyoroti sifat interpretatif dari analisis antropologi. Ini tidak berarti bahwa studi tentang kebudayaan tidak valid, tetapi ini mengakui bahwa pengetahuan yang kita hasilkan selalu bersifat parsial dan diposisikan. Ini mendorong para antropolog untuk lebih sadar akan posisi mereka sendiri dan untuk menyertakan suara-suara dari orang-orang yang mereka pelajari dalam tulisan mereka.
Pada akhirnya, pengakuan bahwa kebudayaan adalah “buatan manusia” dan terus-menerus dibuat ulang adalah sebuah wawasan yang memberdayakan. Ini berarti bahwa jika kita tidak menyukai aspek-aspek tertentu dari budaya kita, kita memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Antropologi modern bukan lagi hanya tentang mempelajari masyarakat “tradisional” atau “eksotis”. Ia adalah ilmu modern tentang keragaman perilaku manusia yang menganalisis keadaan budaya kontemporer dan masa depan, mengakui bahwa banyak masalah global saat ini, dari politik identitas hingga krisis lingkungan, pada dasarnya adalah tantangan budaya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa kritik utama terhadap definisi kebudayaan dari E.B. Tylor?
Kritik utama terhadap definisi Tylor dari perspektif modern adalah bahwa ia cenderung menyajikan kebudayaan sebagai entitas yang statis, homogen, dan terikat pada satu masyarakat. Pandangan kontemporer lebih menekankan sifat kebudayaan yang dinamis, cair, penuh kontradiksi, dan terus-menerus melintasi batas-batas geografis melalui proses globalisasi.
Apa itu enkulturasi?
Enkulturasi adalah proses seumur hidup di mana seorang individu belajar dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan perilaku dari kebudayaan tempat mereka dibesarkan. Ini adalah proses pembelajaran sosial yang terjadi baik secara sadar (melalui pengajaran langsung) maupun tidak sadar (melalui pengamatan dan interaksi sehari-hari).
Apa perbedaan antara kebudayaan dan masyarakat?
Secara sederhana, “masyarakat” (society) mengacu pada sekelompok orang yang terorganisir yang berinteraksi satu sama lain. Ini adalah tentang struktur sosial dan hubungan. “Kebudayaan” (culture) mengacu pada cara hidup yang dipelajari dan dibagikan oleh kelompok orang tersebut, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, bahasa, dan praktik mereka. Masyarakat adalah wadahnya, dan kebudayaan adalah isinya.
Apa itu glokalisasi?
Glokalisasi adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana fenomena global diadaptasi dan diinterpretasikan secara berbeda di tingkat lokal. Ini adalah gabungan dari “globalisasi” dan “lokalisasi”. Contohnya adalah bagaimana restoran cepat saji global seperti McDonald’s menyesuaikan menunya dengan selera lokal di berbagai negara. Ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak selalu menciptakan keseragaman budaya.
Bagaimana antropologi relevan di dunia modern saat ini?
Antropologi sangat relevan karena ia memberikan alat untuk memahami keragaman manusia dan kompleksitas masalah global. Para antropolog bekerja di berbagai bidang, mulai dari riset pasar (memahami perilaku konsumen), kesehatan masyarakat (merancang intervensi yang peka budaya), hingga pengembangan internasional dan resolusi konflik. Dengan memahami “lensa” budaya yang berbeda, kita dapat merancang solusi yang lebih efektif dan manusiawi untuk tantangan-tantangan kontemporer.
Referensi
- Sir Edward Burnett Tylor – Britannica
- Defining Culture – Lumen Learning, Cultural Anthropology
- The Culture Concept – Social Sci LibreTexts
- Habitus – Oxford Bibliographies in Anthropology
- Glocalization: Definition and Examples – ThoughtCo.
- Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia – Sensus Penduduk 2010, BPS

Business & Whitelabel
Reflect your company’s culture.
Cerminkan budaya perusahaan Anda.

Book Repair & Conservation
Preserve culture’s timeless artifacts.
Lestarikan artefak budaya abadi.